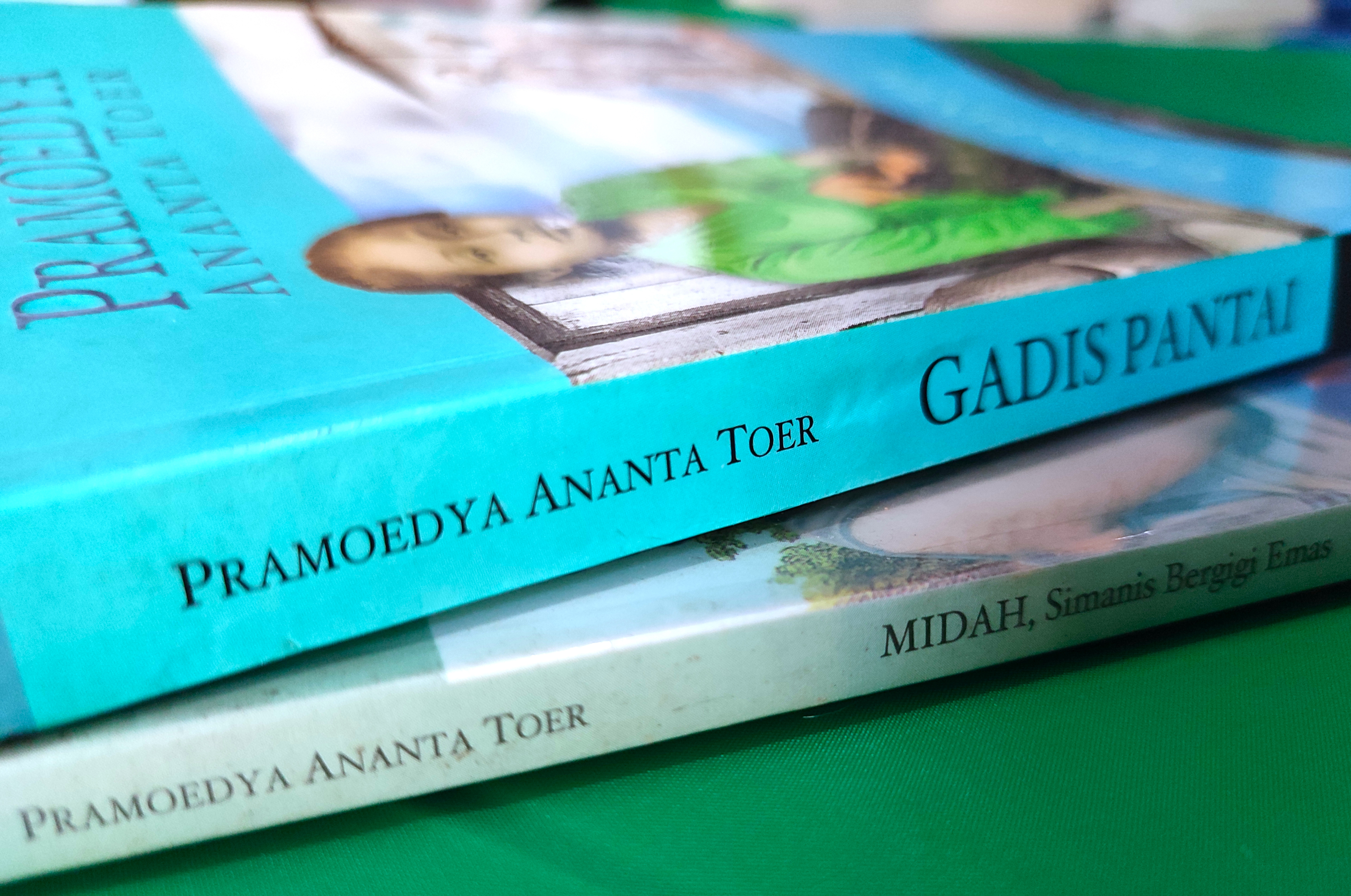“Mbok, kau mau lawan kejahatan ini dengan tanganmu, tapi kau tak mampu. Maka itu kau lawan dengan lidahmu. Kaupun tak mampu. Kemudian kau cuma lawan dengan hatimu. Setidak-tidaknya kau melawan.”
– Pramoedya Ananta Toer, dalam novel Gadis Pantai
Otoritas berkali-kali memenjarakan tubuh Pram. Seratus tahun setelah kelahirannya, gagasan dan tulisannya tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya abadi.
Pram: Penulis asal Indonesia yang mendunia
Pramoedya Ananta Mastoer, atau yang dikenal dengan nama Pramoedya Ananta Toer atau Pram, lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925. Ayahnya seorang guru, dan ibunya seorang penjual nasi. Kepada Koesalah Soebagyo Toer, adiknya, Pram bercerita bahwa ia sudah menulis sejak kelas 3 SD.
Kini, setidaknya 50 novel karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Melalui karya-karyanya, Pram menuangkan kritik sekaligus keberpihakannya kepada perlawanan atas berbagai ketidakadilan: diskriminasi ras dan kelas; penjajahan dan penindasan; serta pembatasan kebebasan berpikir dan berpendapat.
Tetap menulis meski dibungkam
Selama 81 tahun hidupnya, setidaknya 18 tahun dihabiskannya di balik jeruji besi. Pram dikurung di setidaknya tujuh penjara. Dari satu penjara ke penjara lain, Pram tetap menulis.
Pada tahun 1947-1949, Pram ditawan oleh otoritas Belanda di Penjara Salemba, Jakarta, karena dituduh terlibat dalam aksi perlawanan terhadap aksi militer Belanda. Di penjara ini, Pram menulis novel pertamanya, Sepuluh Kepala Nica.
Setelah Agresi Militer Belanda II berakhir, Pram dibebaskan. Namun, pada 1949, Pram kembali ditangkap oleh pasukan tentara kolonial Belanda dan ditahan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Pada 1951, Pram dipindahkan dari Bukittinggi ke Penjara Glodok di Jakarta. Pram mendekam selama satu tahun sebelum dibebaskan pada 1952.
Pada tahun 1958, Pram bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kesenian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Atas keterlibatannya dalam organisasi ini, pada masa Orde Baru, Pram ditangkap tanpa proses peradilan di tahun 1969. Ia diasingkan ke Pulau Buru, Maluku.
Di pengasingan, Pram dan ribuan tahanan hati nurani lainnya hidup dalam kondisi memprihatinkan, bergantung pada hasil bumi setempat untuk bertahan hidup dan makan.
Setelah sepuluh tahun diasingkan di Pulau Buru, Pram dipindahkan ke Penjara Cipinang di Jakarta. Beberapa buku dalam tetralogi novel Pulau Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca ditulis Pram saat dalam masa pengasingan ini.
Pada tahun 1980, Pram dipindahkan ke Penjara Nirbaya (sekarang Lapas Narkotika Jakarta). Di situ, ia dipenjara selama 8 tahun sebelum akhirnya dibebaskan pada 1988.
Pada tahun 1995, Pram kembali ditangkap atas tuduhan makar. Ia dibebaskan setahun kemudian. Selama Pram dipenjara, Maemunah, istri Pram, membesarkan kedelapan anak mereka. Dalam kondisi terjangkit tuberkulosis, Maemunah, bersama anak-anaknya, tinggal dengan kerabatnya.
Pram, Amnesty International, dan desakan pembebasan tahanan hati nurani
Saat Pram dipenjara di Pulau Buru, Amnesty International mendesak pembebasan semua tahanan hati nurani yang dipenjara karena dituduh berafiliasi dengan partai komunis, termasuk Pram.
Pada masa itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melarang setiap tindakan yang dianggap menggoyahkan kestabilan politik negara.
Tindakan yang dimaksud subversif di antaranya: menggulingkan pemerintahan yang sah, memutarbalikkan Pancasila atau haluan negara, menyebar rasa permusuhan dan perpecahan, menyatakan simpati terhadap suatu negara yang bermusuhan dengan Indonesia, merusak fasilitas umum, melakukan kegiatan mata-mata, dan sabotase. Hukumannya dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara hingga 20 tahun.
Selama masa Orde Baru pula, Kejaksaan Agung menerbitkan surat larangan untuk membaca, memiliki, ataupun menjual buku-buku karya Pram. Karya-karya Pram dianggap subversif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta mengancam kestabilan negara.
Meski Undang-Undang itu dicabut pada tahun 1999, ribuan orang korban yang dituduh melakukan tindakan subversi telah dipenjara tanpa peradilan dan kehilangan haknya. Pram salah satunya.
Pada tahun 1973, saat Pram masih dalam pengasingan di Pulau Buru, tekanan dari dunia internasional menyebabkan Pram diizinkan untuk kembali menulis.
Dalam Catatan atas Catatan yang dimuat dalam Lied van een Stomme atau edisi Belanda dari Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, satu-satunya karya non-fiksi Pram, ia menulis:
“Terima kasih tak terhingga, dan memang jadi haknya, adalah pada semua dan setiap orang, yang karena solidaritas internasional dan manusiawinya memungkinkan adanya kelonggaran menulis dalam pembuangan sejak 1973, khususnya Amnesti Internasional, Komite Indonesia, (badan apa lagi?)…”
Dalam laporan Amnesty International tahun 1977 tentang situasi HAM Indonesia, Amnesty menyerukan gentingnya pembebasan setiap tahanan hati nurani. Setiap tahanan hati nurani harus mendapat akses ke peradilan yang terbuka, adil, dan segera, atau dibebaskan dengan segera tanpa syarat.

Kompas, dalam wawancara tanggal 21 Desember 1979 mencatat, hal yang paling diinginkan Pram setelah bebas dari Pulau Buru adalah berkumpul bersama keluarga. Pram ingin memeluk anaknya, Yudistira, yang ketika ia ditangkap oleh pemerintah Orde Baru, baru berumur dua bulan.
Pram dan kebebasan berekspresi
Pram tutup usia pada 30 April 2006. Tubuhnya lekang oleh waktu, tapi gagasannya abadi.
Dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, kumpulan memoar tulisannya selama sepuluh tahun di Pulau Buru, ia menulis:
“Dahulu aku punya anggapan, yakni waktu berumur duapuluhan, bahwa orang yang cukup menjadi manusia yang baik kalau dia menjadi pasifis yang baik. Ternyata anggapan itu keliru, karena manusia itu ada justru karena keterangan dirinya sebagai manusia. Sedang keterangan diri itu meliputi seluruh kehidupan: kebudayaan, peradaban, tradisi, sejarah, cita-cita dan kenyataannya, kondisi fisik dan psikis, ekologi.” (hal.290).
Melalui buah pikirannya yang menjelma jadi karya-karyanya yang mendunia, Pram menceritakan bagaimana manusia tanpa kemanusiaan menjadi tubuh tanpa jiwa, dan bagaimana manusia tanpa kebebasan telah direnggut dari apa yang semestinya menjadi haknya: hak asasi manusia.
Hari ini, kebebasan berekspresi kita masih belum sepenuhnya dihormati negara. Karya-karya Pram seharusnya jadi pengingat bagi kita semua: kebebasan yang merupakan hak asasi manusia harusnya dihormati, alih-alih dibungkam.
Sumber:
Buku:
Pramoedya Ananta Toer (1988). Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Diterbitkan oleh Penerbit Hasta Mitra, September 2000.
Laporan:
Amnesty International (1977). Indonesia: An Amnesty International Report.
Artikel berita:
Kompas.com (2023, 15 Juni). Pasal Subversi Era Orde Baru.
Tempo.co (2024, 1 Mei). 18 Tahun Kepergian Pramoedya Ananta Toer: Kisah dari Penjara ke Penjara.